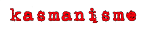[03.04.2007] Islam Sebagai Teks
Dalam tulisannya, Novriantoni[1] mengatakan “Faktanya, siapapun yang berbicara ihwal keagamaan (terutama Islam), selalu saja dihadang tantangan berarti tentang bagaimana laiknya memperlakukan teks-teks agama yang diyakini merupakan rujukan paling otentik guna menanggapi berbagai problem hidup. Fakta demikian sudah dialami banyak pemikir besar Islam. Sudah lama, mereka mencermati adanya jurang pemisah (alhuwwah al-fâshilah) antara teks dengan konteks atau sejarah umat manusia”.
Dengan melihat realitas ini, maka sudah menjadi suatu yang shahih bahwa untuk berbicara tentang Islam, maka pada saat yang sama sebenarnya pembicaraan itu membahas tentang segepok teks.bahkan sebagaimana disinyalir oleh Yudi Latif[2], dalam berdialektika dengan teks, umat Islam terpecah menjadi dua model fundamentalisme, yaitu fundamentalis literal berusaha/mengusahakan diri untuk “dipeluk teks”, sementara “fundamentalis liberal”, getol “memerkosa teks”.
Agar perbincangan tentang Islam yang diposisikan sebagai teks, alangkah baiknya kita melihat sejenak ulasan Nasr Hamid tentang teks sebagai berikut :
Untuk membangun sebuah dialektika yang sehat antara manusia sebagai penafsir dengan Islam sebagai teks (diwakili oleh Al Qur’an), maka alangkah indahnya perkataan Ali bin Abi Thalib, “Alqur’an tak pernah bicara, manusialah yang membunyikannya” (lâ lanthiw, innamâ yanthiq bihi al-rijâl).
Beragamnya paradigma dan sudut pandang yang digunakan dalam menginterpretasi Islam telah melahirkan corak Islam yang menarik dan penuh warna-warni. Islam warna-warni ini bekerja dengan logika sederhana seperti yang disinyalir oleh Muhamad Kasman[4], Islam warna-warni ini akan menolak logika kesamaan dan proses asimilasi yang satu arah. Dengan adanya ruang Islam yang warna-warni seperti ini, maka Islam menjadi begitu ramai dan indah. Penuh nuansa yang begitu eksotik untuk dielaborasi lebih jauh.
Kompleksitas penghampiran ini, memberi secercah harapan bagi kemungkinan kebangkitan Islam di masa yang akan datang. Hal ini karena kompleksitas ini mengindikasikan adanya keseriusan dari para intelektual Islam dalam melakukan upaya memajukan Islam sebagai tawaan bagi perubahan peradaban dunia kearah yang lebih baik di masa yang akan dating.
Bangunan pemikiran Islam yang begitu beragam menjadi khasanah yang tak ternilai harganya dalam menjadi alat atau perangkat untuk makin mendekatkan Islam kedalam jantung realitas umat. Secara sederhana, pemikiran Islam kontemporer dapat terpetakan secara sederhana seperti bagan sederhana seperti ini (meskipun ini terkesan agak simplifikatif). Bagan ini bukanlah pemetaan yang paten, melainkan sebagai sebuah upaya abstraksi intelektual yang mempermudah pemahaman.
Pembaharuan pemikiran Islam yang telah dipaparkan tersebut diatas, hampir semuanya hanyalah merupakan sebuah proses involusi secara terus menerus. Hal ini karena bangunan kerangka pikir yang mereka gunakan serupa meskipun tak sama. Kerangka pikir yang dimaksud adalah adanya dorongan untuk tetap mencari sentrum kebenaran.
Corak umum dari hampir semua pembaharuan pemikiran dalam Islam hanyalah berkisar pada modernisme dan puritanisme. Kalau modernisme menempatkan metanarasi modernitas barat sebagai sentrum kebenarannya, maka puritanisme memposisikan kebenaran sebagai milik sekelompok ulama sebagai sentrum. Kondisi yang tetap memposisikan adanya sentrum kebenaran mutlak yang bersifat metanarasi menyebabkan begitu sulit menemukan adanya ruang partisipasi aktif umat beragama di dalamnya.
Kemungkinan adanya ruang partisipasi itu sebenarnya sudah jauh-jauh hari dibuka oleh para pemikir-ulama melalui proses pribumisasi Islam atau melakukan sintesa kreatif antara Islam dan budaya lokal yang menghasilkan Islam lokalitas. Inilah yang kemudian dilabeli sebagai pemikir-pemikir post-tradisonalisme Islam. Namun cara berfikir seperti inilah yang rentan dicap sebagai gerakan takhyul, bid’ah dan khurafat.
Padahal ruang apresiasi yang lebih luas dan memungkinkan adanya tawar menawar antara umat dengan pilihan religiusitasnya menjadi lebih terbuka. Ruang yang memposisikan spiritualitas sebagai sebuah wilayah yang begitu privat, sehingga kebenaran-kebenaran spiritualitas ini menjadi sebuah wilayah little narrative dan bersifat kesadaran non-diskursif foucauldian.
Secercah harapan itu adalah semangat untuk tanpa henti secara terus-menerus melakukan elaborasi mendalam atas doktrin Islam dan kemudian dituliskan dan disebarluaskan ditengah-tengah umat. Harapan itu adalah keberanian untuk menulis, menulis dan menulis. Meskipun bagi Fahruddin Nasrullah AM[5], “menulis tak lain hanya setitik upaya untuk menghancurkan setiap suara, segala asal usul. Menulis adalah pengebirian; ikhtiar untuk memiuh hal-ihwal”
Namun memang seperti itulah adanya, kita tidak perlu mengerti kenapa kita menulis, yang kita butuhkan hanya tahu dan tahu bahwa kita sedang menulis. Seperti diungkapkan oleh Gao Xingjian[6] “pada kenyataannya aku sama sekali tidak mengerti; sama sekali tidak. Begitulah”. Akhirnya aku teringat oleh sebuah nyanyian yang selalu didendangkan oleh nenekku tercinta ketika aku sulit tidur;
Semangat itu adalah gairah yang mampu membuat bertunasnya kembali ranting yang kering. Carilah semangat itu dengan menulis dan menulis.
Berbicara tentang Islam dan
mungkin agama apapun yang lain, maka hadangan utama yang pasti dihadapi adalah
kuatnya tarikan teks yang mejadi referensi utama dalam mengulas pokok-pokok
ajaran agama tersebut. Secara khusus Islam, bahkan Nasr Hamid Abu
Zaid dalam Mafhûm al-Nash, menyebut peradaban umat Islam sebagai
“peradaban teks” (hadlârah al-nash).
Ini mungkin untuk menunjukkan betapa kuatnya teks mempengaruhi kerangka pikir
umat dalam berdialektika dengan konteksnya.
Dalam tulisannya, Novriantoni[1] mengatakan “Faktanya, siapapun yang berbicara ihwal keagamaan (terutama Islam), selalu saja dihadang tantangan berarti tentang bagaimana laiknya memperlakukan teks-teks agama yang diyakini merupakan rujukan paling otentik guna menanggapi berbagai problem hidup. Fakta demikian sudah dialami banyak pemikir besar Islam. Sudah lama, mereka mencermati adanya jurang pemisah (alhuwwah al-fâshilah) antara teks dengan konteks atau sejarah umat manusia”.
Dengan melihat realitas ini, maka sudah menjadi suatu yang shahih bahwa untuk berbicara tentang Islam, maka pada saat yang sama sebenarnya pembicaraan itu membahas tentang segepok teks.bahkan sebagaimana disinyalir oleh Yudi Latif[2], dalam berdialektika dengan teks, umat Islam terpecah menjadi dua model fundamentalisme, yaitu fundamentalis literal berusaha/mengusahakan diri untuk “dipeluk teks”, sementara “fundamentalis liberal”, getol “memerkosa teks”.
Agar perbincangan tentang Islam yang diposisikan sebagai teks, alangkah baiknya kita melihat sejenak ulasan Nasr Hamid tentang teks sebagai berikut :
Alqur’an adalah
teks yang (hanya) beku, tetap dan statis dari sisi pengucapan verbalnya (min
haits al-manthûq), itu karena dia sudah menjadi mushaf yang
dibakukan. Sedang secara konsepsi (al-mafhûm), dia sudah lepas
dari sifat statisnya; dia dinamis, plural dan relatif dari segi penafsirannya.
Sejak mula-mula teks yang ilahi dibumikan, lalu dibaca secara verbal,
(perdananya oleh nabi) posisinya sudah bergeser dari teks ilahi yang statis,
mutlak, tidak berubah, menjadi konsepsi atau teks manusiawi (yata’annas)
yang relatif, dan selalu menyemangati perubahan-perubahan[3]
Untuk membangun sebuah dialektika yang sehat antara manusia sebagai penafsir dengan Islam sebagai teks (diwakili oleh Al Qur’an), maka alangkah indahnya perkataan Ali bin Abi Thalib, “Alqur’an tak pernah bicara, manusialah yang membunyikannya” (lâ lanthiw, innamâ yanthiq bihi al-rijâl).
Kompleksitas Penghampiran
Dalam melakukan upaya interpretasi terhadap Islam sebagai
sebuah bangunan teks yang membutuhkan penjelasan lanjutan agar nilai yang
dimuatnya tetap kontekstual, dikalangan para pemikir Islam telah terbangun
dengan begitu ramainya paradigma dan sudut pandang yang digunakan dalam proyek
penghampiran ini.
Beragamnya paradigma dan sudut pandang yang digunakan dalam menginterpretasi Islam telah melahirkan corak Islam yang menarik dan penuh warna-warni. Islam warna-warni ini bekerja dengan logika sederhana seperti yang disinyalir oleh Muhamad Kasman[4], Islam warna-warni ini akan menolak logika kesamaan dan proses asimilasi yang satu arah. Dengan adanya ruang Islam yang warna-warni seperti ini, maka Islam menjadi begitu ramai dan indah. Penuh nuansa yang begitu eksotik untuk dielaborasi lebih jauh.
Kompleksitas penghampiran ini, memberi secercah harapan bagi kemungkinan kebangkitan Islam di masa yang akan datang. Hal ini karena kompleksitas ini mengindikasikan adanya keseriusan dari para intelektual Islam dalam melakukan upaya memajukan Islam sebagai tawaan bagi perubahan peradaban dunia kearah yang lebih baik di masa yang akan dating.
Bangunan pemikiran Islam yang begitu beragam menjadi khasanah yang tak ternilai harganya dalam menjadi alat atau perangkat untuk makin mendekatkan Islam kedalam jantung realitas umat. Secara sederhana, pemikiran Islam kontemporer dapat terpetakan secara sederhana seperti bagan sederhana seperti ini (meskipun ini terkesan agak simplifikatif). Bagan ini bukanlah pemetaan yang paten, melainkan sebagai sebuah upaya abstraksi intelektual yang mempermudah pemahaman.
Pemetaan diatas menunjukkan
begitu ramainya warna Islam yang merupakan hasil interpretasi dari berbagai
sudut pandang yang digunakan. Berikut penjelasan sederhana dari bagan diatas :
1.
Tradisional
Corak
pemikiran Islam yang kami defenisikan sebagai corak pemikiran tradisional
adalah pemikiran islam yang terbangun pada zaman klasik Islam. Corak pemikiran
Islam model ini, mengedepankan cara interpretasi Islam secara filosofis dengan
pengaruh kental dari pemikiran filosof Yunani. Pada fase ini pemikiran Islam
yang terkenal adalah corak pemikiran Peripatetik (masyaiyyah), Teologi (kalam),
Sufi atau Tashawuf (irfan), Iluminasi (isyraq) sampai Teosophy
Transenden (al hikmah muta’aliyah).
Pemikiran
Islam yang berkembang pada masa itu sungguh bervariasi sehingga menunjukkan
sebuah warna Islam yang beragam. Pada abad ke 2-5 hijriyah-lah puncak
pencapaian Islam akan perkembangan ilmu pengetahuan yang membuat peradaban
Islam disegani di seluruh dunia pada masanya. Hal ini karena penghargaan Islam
terhadap berbagai macam teori pengetahuan dan pemikiran berhasil didamaikan
dengan doktrin Islam.
Pada masa
inilah kita mengenal Ibn Sina, Al Farabi, Ibn
Arabi, Al Ghazali, Suhrawardi, Ibn Rusyd
dan Mulla Sadra (yang terakhir ini tidak begitu popular).
Inilah fase pemikiran yang kami kategorikan sebagai pemikir tradisional Islam (atau
lebih dikenal sebagai pemikir klasik Islam). Dalam perkembangan berikutnya,
pemikiran tradisional ini mengalami pasang surutnya di duina pemikiran islam.
Pada fase
selanjutnya, pemikiran tradisionalis Islam ini mengalami metamorfosis dan
melahirkan penerus mereka dalam dua wajah, yaitu :
a.
Neo-Tradisional
Para pemikir neo-tradisional yang
dimaksud adalah para pemikir kontentemporer Islam yang tetap percaya dengan
kemapanan-kemumpunian kebenaran Islam yang diinterpretasi secara filosofis dan
tetap mengacu pada filsafat klasik Islam mulai dari paripatetik sampai
theosophy transenden.
Warna
pemikiran yang tetap bercorak hellenisme Islam ini dapat ditemukan pada
pemikiran Syed Husein Nasr dan Murtadha Mutahhari atau para
pemikir yang yang belakangan terkategorikan dan tenar dengan gelar Mazhab
Qum.
b.
Post-Tradisional
Turunan
kedua dari pemikiran tradisional Islam adalah para pemikir post-tradisional
Islam. Pemikir kelompok ini bukannya berusaha untuk mengkonstruksi Islam dengan
melakukan revitalisasi corak berfikir Islam tradisional, melainkan berusaha
menggali tradisi pemikiran Islam secara menukik-kritis dan kemudian berusaha
melampauinya.
Pemikir
kontemporer yang bisa dikategorikan dalam kelompok ini adalah pemikir Arab
kelahiran Maroko yang bernama Muhammad Abed Al Jabiri. Bangunan
cara berfikir post-tradisional Islam mencoba kembali mengembalikan posisi
tradisi sebagai sesuatu yang hidup dan terus berkembang dan bukan sebagai
sesuatu yang terwariskan begitu saja dari generasi lama ke generasi baru.
2.
Modern
Pemikiran
Modern dalam Islam, muncul kepermukaan belantara pemikiran Islam lebih
merupakan sebuah upaya responsif para intelektual Islam dalam memberikan
jawaban terhadap konteks modernitas yang menjadi warna dominan dunia
kontemporer. Respon para intelektual tersebut terhadap bangunan modernitas
terbagi menjadi berbagai corak, ada yang menolaknya secara kritis dengan
meminjam alat analisis sosialis/marxis, sebagian mencoba mendamaikan doktrin
islam dengan hakekat pencerahan dan sebagian lagi menolak mentah-mentah dan
menganggap modernitas sebagai senjata setan yang sangat berbahaya.
Namunpun
bergitu, usaha para intelektualitas Islam ini dalam melakukan pergulatan hidup
yang demikian “liat” patut mendapatkan apresiasi intelektual yang sepadan, hal
ini karena corak pemikiran ini telah melahirkan beberapa tokoh yang berhasil mempengaruhi
jalannya sejarah Islam bahkan sejarah dunia secara fenomenal.
Beberapa nama
pemikir dan pelaku proyek pembaharuan Islam di zaman modern tersebut adalah Muhammad
b. Abd Al-Wahhab, Syaikh ‘Utsman, al-Hajj ‘Umar Tal,
Sayyid Ahmad al-Brelvi, Syah Wali Allah, Jamaluddin al-Afgani,
Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Rifa’ah al-Tahtawi, ‘Ali
Abd al-Razik, Sayyid Ahmad Khan, Abd Kalam Asad, Muhammad
Iqbal. Demikian beberapa nama yang patut untuk disebut, dan satu hal yang
patut mendapat perhatian lebih bahwa hampir semua pemikir ini melakukan
rekonstruksi pemikiran Islam sebagai sebuiah bentuk respon intelektual atas
gerak laju modernitas yang dianggap merugikan gerakan Islam. Sehingga nama-nama
yang disebut tersebut adalah orang-orang yang memimpin pergerakan negaranya
melawan kolonialisme dan imprealisme.
a.
Sosialis/Marxis
Perkembangan selanjutnya dalam
pemikiran modern Islam, akan ditemukan adanya kait-kelindan antara ghirah
perlawanan Islam dengan daya kritis pemikir-pemikir sosialis-marxis. Hal ini
bukan berarti bahwa corak pemikiran ini terpengaruh sepenuhnya oleh pemikiran
sosialis-marxis, melainkan hal ini menunjukkan adanyasebuah dialektika
intelektual dan melahirkan sebuah sintesa kreatif pemikiran tanpa meninggalkan
diktrin dasar Islam.
Pemikir yang bisa dikategorika dalam
pemikiran ini adalah Ali Syari’ati, Ashgar Ali Engineer,
Soekarno. Merekalah para pemikir yang mencoba menghadirkan Islam sebagai
sebuah doktrin histories dan memiliki peran riil dalam sejarah kehidupan
kemanusiaan. Islam dijadikan sebagai pendorong perubahan menuju kearah yang lebih baik.
Dalam perkembangannya, corak pemikiran
ini mengental dalam sebuah kategorisasi intelektual, bangunan Islam
transformatif, sebuah corak berfikir yang percaya dan mempraxiskan Islam
sebagai ruh dari proses transformasi sosial. Pemikir Islam kontemporer yang
paling sering disebut adalah Hasan Hanafi dengan Al Yasar Al
Islami-nya, meskipun beliau tetap mengangap dirinya seorang fundamentalis
b.
Neo-Modernis
Pemikiran modernis Islam mengalami
metamorfosis secara sempurna dalam pemikiran para neo-modernis Islam yang
mengelaborasi lebih mendalam doktrin Islam dalam perspektif teori-teori modern.
Corak berfikir seperti ini dapat ditemukan dalam pemikiran-pemikiran Fazlur
Rahman yang kemudian dilanjutkan oleh muridnya, Nurcholish Madjid.
Neo-modernis Islam membangun sebuah
model doktrin Islam yang dianggap pas dengan perkembangan mutakhir masyarakat
modern. Pemikiran ini lebih menekankan pengamalan substansi doktrin Islam yang
diseuaikan dengan konteks dimana ajaran itu akan diterapkan.
Dalam perkembangan mutakhir, gerakan
Intelektual Islam ini memunculkan corak berfikir Islam yang dikenal dengan nama
Islam Liberal. Pemikir Islam Liberal yang bisa disebut adalah Ulil Abshar
Abdalla. Pemikran Islam liberal mempersoalkan berbagai sisi doktrin
Islam yang merambah wilayah publik dan mencoba mendorongnya kembali kewilayah
privat.
c.
Radikal
Kelompok radikal adalah satu faksi
pemikiran Islam yang mencoba berdialektika dengan modernitas. Gerakan pemikiran
ini memilih untuk menegakkan puritanisme Islam sebagai jawaban atas gerak laju
modernitas. Keyakinan ini dibangun berdasar pada doktrin Islam bahwa islam
adalah agama yang sempurna dan sebagai agama untuk segala zaman dan segala
situasi.
Corak pemikiran ini dapat ditemukan dalam
Hasan Al-Banna, Sayyid Qutb, Abu A’la al-Maududi, Taqiyuddin
An Nabhani. Dalam kerangka logika Islam radikal, nambak adanya sebuah
keteguhan hati untuk mengamalkan Islam dengan apa adanya, sebagaimana
Rasulullah mengamalkannya. Perjuangan gerakan ini mengejawantah dalam
gerakan-gerakan Islam, seperti Ikhwanul Muslimin, Jamaat-I-Islami dan Hizbut
Tahrir.
Involusi;
Pembaharuan Tanpa Perubahan
Dalam
teori tentang perubahan, lazimnya perubahan itu terjadi dengan dua jalan, jalan
revolusi atau jalan evolusi. Perubahan disebut bila terjadi secara cepat,
sementara dia akan disebut evolusi kalau dia terjadi secara lambat atau
pelan-pelan. Namun disamping itu ternyata ada yang disebut dengan involusi.
Involusi adalah sebuah proses perubahan yang sebenarnya tidak berubah. Artinya
bahwa secara sepintas terlihat adanya perubahan, tapi bila ditilik secara
seksama maka yang terjadi hanyalah perubahan wajah tanpa perubahan karakter.
Pembaharuan pemikiran Islam yang telah dipaparkan tersebut diatas, hampir semuanya hanyalah merupakan sebuah proses involusi secara terus menerus. Hal ini karena bangunan kerangka pikir yang mereka gunakan serupa meskipun tak sama. Kerangka pikir yang dimaksud adalah adanya dorongan untuk tetap mencari sentrum kebenaran.
Corak umum dari hampir semua pembaharuan pemikiran dalam Islam hanyalah berkisar pada modernisme dan puritanisme. Kalau modernisme menempatkan metanarasi modernitas barat sebagai sentrum kebenarannya, maka puritanisme memposisikan kebenaran sebagai milik sekelompok ulama sebagai sentrum. Kondisi yang tetap memposisikan adanya sentrum kebenaran mutlak yang bersifat metanarasi menyebabkan begitu sulit menemukan adanya ruang partisipasi aktif umat beragama di dalamnya.
Kemungkinan adanya ruang partisipasi itu sebenarnya sudah jauh-jauh hari dibuka oleh para pemikir-ulama melalui proses pribumisasi Islam atau melakukan sintesa kreatif antara Islam dan budaya lokal yang menghasilkan Islam lokalitas. Inilah yang kemudian dilabeli sebagai pemikir-pemikir post-tradisonalisme Islam. Namun cara berfikir seperti inilah yang rentan dicap sebagai gerakan takhyul, bid’ah dan khurafat.
Padahal ruang apresiasi yang lebih luas dan memungkinkan adanya tawar menawar antara umat dengan pilihan religiusitasnya menjadi lebih terbuka. Ruang yang memposisikan spiritualitas sebagai sebuah wilayah yang begitu privat, sehingga kebenaran-kebenaran spiritualitas ini menjadi sebuah wilayah little narrative dan bersifat kesadaran non-diskursif foucauldian.
Secercah
Harapan
Dalam
ranah keragaman cara pandang dan cara tilik terhadap Islam sebagai teks yang
membutuhkan interpretasi agar dia mampu berdialektika dengan zaman dimana dia
akan dipraksiskan maka akan ditemukan setitik cahaya yang bisa menjanjikan
harapan besar bagi masa depan Islam. Dibutuhkan keberanian untuk membaca Islam
sebagai teks dan keberanian untuk mendedahkanya ditengah umat.
Secercah harapan itu adalah semangat untuk tanpa henti secara terus-menerus melakukan elaborasi mendalam atas doktrin Islam dan kemudian dituliskan dan disebarluaskan ditengah-tengah umat. Harapan itu adalah keberanian untuk menulis, menulis dan menulis. Meskipun bagi Fahruddin Nasrullah AM[5], “menulis tak lain hanya setitik upaya untuk menghancurkan setiap suara, segala asal usul. Menulis adalah pengebirian; ikhtiar untuk memiuh hal-ihwal”
Namun memang seperti itulah adanya, kita tidak perlu mengerti kenapa kita menulis, yang kita butuhkan hanya tahu dan tahu bahwa kita sedang menulis. Seperti diungkapkan oleh Gao Xingjian[6] “pada kenyataannya aku sama sekali tidak mengerti; sama sekali tidak. Begitulah”. Akhirnya aku teringat oleh sebuah nyanyian yang selalu didendangkan oleh nenekku tercinta ketika aku sulit tidur;
Iyya teppaja kusappa
Paccolli’
lolo engngi
Aju
marakko’E
Semangat itu adalah gairah yang mampu membuat bertunasnya kembali ranting yang kering. Carilah semangat itu dengan menulis dan menulis.
[1]
Novriantoni, Berinteraksi dengan Teks: Visi Progresif Islam, www.islamlib.com
[2]
dalam Fundamentalis
Literal versus Fundamentalis Liberal, Koran Tempo, Novermber 2002
[3]
Abu Zaid, Naqd al-Khitâb al-Dînî;
1995 : 126
[4]
Kasman. Muhammad, Islam
Warna-warni; Mozaik Syariat Islam Ditengah Multikulturalisme, dalam jurnal
texere volume I Ramadhan 1424 H/November 2003 M, Makassar, Lingkar Studi Net
Tamalanrea dan HMI MPO Komisariat Pelangi Tamalanrea, hal. 69
[5] de
Cervantes. Miguel. Petualangan Don Quixote, Yogyakarta, Sadasiva,
Agustus 2003, Cet. I. hal vi.
[6] Xingjian.
Gao, Gunung Jiwa, Yogyakarta, Jalasutra, Januari 2003, Cet I, hal 713