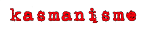Ruang multikultural adalah sebuah ruang kontestasi, demikian seloroh seorang teman
ketika wacana multikulturalisme mengemuka di dunia intelektual sosial-budaya
era 90-an. Wacana ini hampir menjadi wacana dominan yang tak terbantahkan
ketika didedahkan sebagai solusi atas berbagai macam perbedaan (difference)
dan keberagaman (diversity) yang merupakan realitas masyarakat global (global
society). Multikulturalisme menjadi semacam manajemen perbedaan untuk
menjaga keharmonisan dan dinamisasi kehidupan sosial masyarakat.
Multikultural, menurut Ahmad Baso1, berwujud menjadi sebuah gerakan. Dengan defenisi seperti ini, maka multikultural harus bisa dibedakan dengan realitas budaya yang plural. Multikultural merupakan sebuah proyek atau usaha sadar untuk mengatur dan mendinamisasi hubungan (relation) antar kultur, sementara plural hanyalah sebuah kondisi yang sudah ada sebagai realitas. Dengan demikian --masih menurut Ahmad Baso, gerakan multikulturalisme merupakan proyek multidimensional yang melibatkan berbagai etnis dan berbagai macam kegiatan.
Sementara itu, Yasraf Amir Piliang2 mengatakan bahwa multikulturalisme adalah sebuah relasi pluralitas yang di dalamnya terdapat problem minoritas (minority groups) vs mayoritas (mayority group), yang di dalamnya ada perjuangan eksistensial bagi pengakuan, persamaan (equality), kesetaraan, dan keadilan (justice). Beliau juga membedakannya dari pluralisme yang diartikannya sebagai pandangan yang menghargai kemajemukan, serta penghormatan terhadap sang lain yang berbeda (the others), membuka diri terhadap warna-warni keyakinan, kerelaan untuk berbagi (sharing), keterbukaan untuk saling-belajar (inklusivisme), serta keterlibatan diri secara aktif di dalam dialog dalam rangka mencari persamaan-persamaan (common belief) dan menyelesaikan konflik-konflik.
Lebih jauh, multikultural menjadi ranah tempat berlangsungnya komunikasi, dialektika dan tawar-menawar antarbudaya yang terjadi secara seimbang dan sederajat dalam hal hak-hak dan kewajiban-kewajiban kultural. Bila memang demikian adanya, satu hal yang menarik dalam perbincangan multikulturalisme dalam bingkai kelokalan kita adalah wacana penegakan syariat Islam sebagai sebuah aspirasi kultural yang sedang hangat mencari ruang eksisten.
Dengan wacana multikulturalisme, maka keinginan untuk menegakkan syariat Islam akan mendapat ruang perbincangan yang lebih akademis dan bisa di pertangungjawabkan secara ilmiah. Multikulturalisme menghendaki kedewasaan dalam menyikapi perbedaan dan keanekaragaman yang ada, namun juga berusaha untuk tidak terjebak pada affirmative action yang merupakan penyelewengan dari multikulturalisme.
Masalah kedua dalam multikulturalisme menurut Manneke adalah ketika multikulturalisme mengalami penyelewengan dan dimanfaatkan untuk menumbuhkan semangat chauvinisme, sukuisme, dan tirani minoritas. Hal ini akan berakibat muncul dan lahirnya sebuah struktur sosial baru yang cendrung memanjakan dan memberi hak khusus kepada kelompok minoritas yang selama ini terbungkam dan terpinggirkan.
Dan problem yang ketiga adalah pemahaman multikulturalisme mengalami reduksi sebagai sekadar kondisi plural, seperti di Indonesia. Kalau pembahasan ini coba dibatasi pada ruang lingkup Indonesia, maka akan ditemukan adanya penyimpangan ini secara nyata. Baik pada persoalan kultural secara luas, maupun pada persoalan agama secara spesifik.
Penyelewengan multikulturalisme menjadi sekadar pluralisme yang terjadi di Indonesia, terutama pada wilayah keagamaan, ini lebih merupakan akibat dari bangunan teologi yang berkembang. Ini pula yang menjadi kendala perguliran wacana syariat Islam. Meminjam pembagian corak teologi Cecelia Lynch4, akan ditemukan betapa corak teologi seseorang atau sebuah komunitas keagamaan maupun kultural akan sangat berpengaruh bagi proyek multikulturalisme.
Corak teologi Cecelia itu adalah pertama, teologi eksklusif. Teologi ini merupakan teologi yang paling ideologis, sifatnya sangat tertutup dan menempatkan teologinya sebagai satu-satunya kebenaran. Kedua, teologi apologetik. Model teologi apologetik tidak se-ekstrim teologi eksklusif, namun mereka tetap berusaha menjelaskan bahwa teologi merekalah yang benar dengan berusaha mencari berbagai macam apologi atau sistem pembenaran.
Ketiga, teologi inklusif. Dalam teologi seperti ini, sudah ada ruang pengakuan terhadap teologi di luarnya, namun kesimpulan akhir akan kebenaran tetap kembali pada dirinya. Teologi lain memang memiliki kebenaran, tetapi intensitas kebenaran teologi lain tetap berada di bawah kebenaran teologinya. Keempat, teologi sinkretis. Teologi yang paling nyeleneh dan cendrung menyederhanakan masalah kebenaran, karena menganggap semua teologi sama saja sehingga lebih baik dan sah bila antar teologi itu ada perkawinan dan pembauran konsep.
Terakhir, kelima¸ teologi pluralis. Teologi model inilah yang paling pas untuk terbangunnya proyek multikulturalisme. Hal ini karena teologi model ini mengakui bahwa setiap teologi memiliki eksistensi masing-masing, namun semuanya berada dalam tahap proses, sehingga dinamisasi dan dialektika yang terwujud dalam bentuk kontestasi dan dialektika antar teologi lebih memungkinkan.
Kalau pemetaan teologi Cecelia Lynch dipakai dalam menyorot bangunan teologi masyarakat Indonesia yang berusaha menegakkan Syariat Islam secara formal, umumnya masih menganut corak teologi eksklusif. Sementara itu sebagian kecil umat Islam yang berpikir inklusif, apologetik bahkan sinkretis, tidak terlalu ngotot, bahkan tema syariat Islam secara formal bukanlah menjadi hal yang urgen bagi mereka. Bahkan kelompok Islam minoritas ini memiliki siasat tersendiri untuk berislam tanpa harus terjebak pada formalisasi syariat.
Kuntowijoyo5, dengan menganalisis kategori-kategori sistem pengetahuan dan formasi sosial, menemukan fase perkembangan umat Islam Indonesia dan merumuskannya dalam sebuah periodisasi sejarah. Periode pertama, beliau menamainya sebagai periode mitos, umat Islam didominasi oleh kesadaran kawulo. Periode kedua, adalah periode ideologi, umat Islam di indonesia masih di“halusinasi” oleh kognisi wong cilik.
Pada periode terakhir, ketiga, mengemuka periode ilmu. Periode ini ditandai dengan masuknya wabah pencerahan Eropa ke Indonesia pada awal abad 20 M. kesadaran yang diinternalisasi umat Islam adalah kesadaran kewargaan. Nah, kalau berbicara model kesadaran mana yang paling potensial untuk sebuah penegakan syariat Islam secara dewasa, maka jawabnya tentu pada kesadaran kewargaan yang berada pada periode ketiga.
Namun sayang sekali karena dampak dari bangunan teologi yang dianut, maka geliat formalisasi syariat Islam yang mengemuka akhir-akhir ini adalah gerakan yang berbasis pada kesadaran yang ideologis. Kalaupun ada upaya menggiringnya menjadi kesadaran kewargaan, itupun hanya bermain pada tataran elite. Sehingga kesadaran umat secara umum masih tetap pada taraf ideologi yang tentunya berjalin berkelindan dengan teologi yang eksklusif.
Bila sudah seperti ini kondisi yang melingkupinya, maka formalisasi syariat Islam, terancam mengalami kegagalan, bahkan dalam sebuah ruang kontestasi yang demikian terbuka yang ditawarkan oleh proyek multikulturalisme. Hal ini karena di dalam bangunan kognisi umat Islam hari ini secara inhern memang termuat ambiguitas konsepsional ketika diperhadapkan dengan wacana multikulturalisme. Wajah umat Islam dengan versi syariat Islam yang di tawarkan akan menyeret wacana multikulturalisme pada jurang bunuh diri.
Dengan nyata akan terlihat bagaimana potensi ambiguitas multikulturalisme akan menjadi kenyataan karena dorongan dan desakan wajah Islam yang ditawarkan, sehingga multikulturalisme akan berakhir dan mengalami proses kematian yang tragis. Sebuah bunuh diri yang nyata. Hasil mimikri6 budaya antara Islam dan multikulturalisme akan melahirkan sebuah masyarakat nekrokultur6.
Mimikri Baru Islam-Multikultural
Upaya penyelamatan terhadap bangunan sosial mutlak harus dilakukan, oleh karena itu gerak masyarakat kearah nekrokultur mutlak harus di hentikan. Namun satu hal yang harus di catatbahwa, untuk menyelamatkan konstruksi sosial, bukanlah dengan cara memberangus hasrat masyarakat untuk melakukan formalisasi syariat Islam ataukah menghentikan proyek multikulturalisme. Karena pemberangusan dan pembungkaman akan melahirkan sebuah bangunan nekrokultura baru. Yang patut dilakukan adalah melakukan mimikri ulang secara kultural terhadap Islam dan multikultural.
Langkah ini dapat dilakukan dengan dua fase. Fase pertama merupakan fase reinterpretasi atas teologi umat Islam dari teologi eksklusif ke arah teologi pluralis, dengan cara “menyeret” umat untuk beranjak dari periode mitos dan ideologi menuju periode ilmu. Untuk membantu usaha ini, tawaran Kuntowijoyo, merupakan tawaran yang menarik untuk di pertimbangkan.
Kuntowijoyo7 menawarkan sebuah konsep “Ilmu Sosial Profetis”, inti dari konsep ini adalah, pertama, melakukan transformasi sosial dan perubahan dengan cara menjelaskan fenomena sosial kemudian mengubahnya, di samping itu, memberikan interpretasi, mengarahkan, serta membawa perubahan bagi pencapaian nilai-nilai yang dianut oleh kaum muslimin sesuai petunjuk Al-Qur’an, yakni emansipasi atau humanisasi, liberasi, dan transendensi8.
Kemudian, inti kedua dari Ilmu Sosial Profetik adalah bagaimana menjadikan al Quran sebagai paradigma. Hal ini ditawarkan oleh Kuntowijoyo melalui sebuah proyek yang digelarinya “Strukturalisme Transendental”. Menurutnya, setiap relitas sosial selalu dikonstruksi oleh mode of thought atau mode of inquiry. Mode of thought mengkonstruksi realitas melalui mode of knowing yang dilahirkannya. Sebuah cara berfikir yang mirip dengan analisis episteme9 Foucauldian.
Disamping itu, satu hal yang sangat penting untuk dilakukan secara internal oleh umat Islam adalah proses desakralisasi kebenaran. Proyek ini menjadi penting, karena bila ini tidak pernah terlaksana, maka selamanya Islam akan dipahami secara eksklusif. Kebenaran yang selama ini terdedahkan di tengah-tengah umat harus bisa dipahami sebagai sekadar hasil konstruksi episteme tertentu. Bahkan, karena kebenaran hanyalah sebagai sebuah produk dari metode interpretasi tertentu, maka maknanya senantiasa tertunda10.
Bila penyelamatan telah dilakukan pada sisi umat Islam, maka sisi yang satunya, yaitu multikulturalisme, juga seharusnya mengalami penyelamatan. Homi Bhabha11 mengatakan bahwa kata “kultur” dalam multikulturalisme, seharusnya jangan dipahami sebagai suatu rujukan identitas yang bersifat apriori, melainkan sebagai aktivitas negosiasi, pengaturan, dan pengesahan tuntutan-tuntutan akan representasi diri yang kolektif, yang tidak hanya saling berkompetisi, namun juga kerap saling bertubrukan12.
Pemahaman seperti ini harus terbangun untuk menghindari membekunya konsep multikulturalisme menjadi segepok ideologi. Di samping itu untuk menahan agar multikulturalisme tidak terjatuh pada sekadar menjadi bangungan pluralisme, maka masih menurut Bhabha, sifat hubungan antar unsur yang terlibat dalam aktivitas itu adalah konfliktual dan kompetitif, bukan harmonis dan konseptual13. Bila semuanya dipahami sebagai konflik dan kompetisi, maka akan ditemukan bahwa multikuluralisme merupakan sesuatu yang hidup dan penuh gairah, serta bukan sekadar sebuah gambaran realitas yang membeku.
Dengan meminjam analisis Kritik Ideologi Jurgen Habermas14, kemudian diperuncing oleh oto-kritik atas multikulturalisme, Cornel West15 menganjurkan agar multikulturalisme jangan dipahami sebagai ideologi, melainkan sebagai sebuah kritik yang mampu menyoroti berbagai persoalan yang terkandung di dalam multikulturalisme sendiri16. Multikulturalisme di samping dipahami sebagai subyek/pelaku analisisi sosial, multikulturalisme juga harus dijadikan sebagai obyek analisa, karena multikulturalisme juga merupakan konsep yang tidak bisa lepas dari konteks sosial maupun historis tertentu.
Islam Warna-Warni, Islam Lokalitas
Bila upaya membangun mimikri baru Islam-Multkultural berhasil, maka akan lahir sebuah wajah syariat Islam yang tidak memberangus multikulturalisme. Bahkan akan lahir sebuah wajah Islam Warna-Warni. Islam-Multikultural akan mengedepankan local content dalam melakukan interpretasi terhadap Islam. Islam yang bercorak lokalitas akan memungkinkan lahirnya kontestasi budaya lokal dari rahim Islam-Multikultural. Islam Warna-Warni ini akan menolak logika kesamaan dan proses asimilasi yang satu arah.
Ada beberapa nilai dasar yang menjadi ciri khas dari Islam Warna-Warni yaitu, pertama tanpa sentrum, kedua, merupakan hasil penghayatan atas local content. Ketiga, berwujud pengetahuan non-diskursif atau kesadaran non-reflektif. Keempat, berlandaskan pada aqidah yang berorientasi praxis-pragmatis. Kelima, merupakan teologi proses.
Islam yang tanpa sentrum memungkinkan merumuskan sebuah bangunan syariat Islam yang tidak berkiblat ke Arab. Jadi ada upaya untuk memisahkan antara nilai Islam dari budaya Arab yang selama ini menjadi ibu kandungnya. Seuah ikhtiar melahirkan interpretasi Islam dalam pangkuan budaya lokal. Islam Warna-Warni memotong model asimilasi budaya satu arah, bahwa untuk menjadi Islam, maka harus menjadi Arab. Posisi Arab sebagai sentrum kebenaran dari nilai Islam harus mengalami delegitimasi dengan mengedepankan penafsir-penafsir lokal yang lebih memahami nalar dan kognisi masyarakat lokal.
Islam Warna-Warni akan mendorong penguatan wilayah feri-feri tanpa harus terjebak pada affirmative action yang cenderung melahirkan kekuasaan otoritatif seorang penafsir sebagai kebenaran tunggal secara apriori dan mutlak. Sebagaimana mafhum, proses representasi menurut Nuhsin Arbabzadah-Green17 bukanlah realitas yang sebenarnya, ia hanya menghadirkan satu potongan atau esensialisasi dari realitas tersebut, yang terkadang penuh reduksi dan menggeneralisasi. Bila posisi setiap representasi adalah sama, maka Islam yang di representasikan oleh budaya Arab, tidak berhak untuk menjadi tafsir tunggal Islam.
Karena setiap bangunan budaya sebagai wilayah feri-feri punya hak yang sama untuk merepresentasikan Islam, maka tentu akan lahir Islam yang concern terhadap local content masing-masing budaya. Dengan terbukanya ruang ini, akan memungkinkan Islam menjadi sebuah ruang penghayatan spirtualitas yang betul-betul dialami secara utuh sebagai proses kemausiaan dalam sebuah proses kemenjadian oleh seorang manusia.
Proses penghayatan yang agak fenomenologi ini, akan mendorong lahirnya bangunan pengetahuan non-diskursif18, sebagai bangunan pengetahuan alternatif yang tidak di produksi oleh sebuah formasi diskursif dominan yang cendrung menghegemoni. Juga penghayatan ini akan melahirkan kesadaran non-reflektif19 sebagai model kesadaran yang tidak berjarak dengan realitas dan merupakan ikhtiar keluar dari belukar kesadaran ideologis yang mengekang dan membeku. Jadi Syariat Islam yang paling riil adalah yang aktual dan teraktualisasi di tengah masyarakat yang lahir dari hasil penghayatan atas realitas spiritual.
Islam Warna-Warni mendorong model aqidah praxis-pragmatis, maksudnya bahwa pada dasarnya tujuan utama dari aqidah adalah praxis atau pragmatis, bukan teoritis, argumentatif maupun retoris. Aqidah harus mampu menjadi landasan gerak dan menggerakkan. Tauhid sebagai doktrin dasar aqidah Islam sudah bukan saatnya lagi berbicara tentang keesaan Tuhan secara njlimet, namun lebih pada tuntutan bagaimana diktum ini mengejawantah dalam realitas lewat wajah kebenaran, keadilan dan spiritualitas.
Sebagaimana dikatakan oleh Abbe Pire20, apa yang menjadi persoalan bukanlah perbedaan antara orang yang beriman dan orang yang tidak beriman, akan tetapi antara siapa yang membela (menjalankan) dan siapa yang tidak membela atau tidak mengamalkan. Kebenaran Aqidah dari Islam Warna-Warni terletak pada tanggungjawab kulturalnya. Bukan pada kekuatan argumentasi kebenaran teoretisnya. Inilah aqidah praxis-pragmatis yang menjadi hakekat Syariat Islam.
Ciri terakhir dari Islam Warna-Warni adalah coraknya sebagai teologi yang hidup dan senantiasa berjalan sebagai proses tanpa henti. Teologi proses dimungkinkan karena indikator kebenaran sebuah teologi terletak pada kemampuannya untuk senantiasa menjawab kebutuhan realitas sosial, sementara itu sebagaimana mafhum, realitas sosial merupakan sesuatu yang hidup, senantiasa berada dalam situasi dan wajah konfliktual serta kompetitif. Kondisi ini menuntut sebuah bangunan kebenaran yang bersifat holistik dengan ciri situasi taksa, samar dan ambigu, namun bernuansa intuitif, mistisis dan lebih estetis[1].
Islam-Multikuluralisme Melalui Seni
Dengan wajah Islam yang warna-warni, maka kemungkinan penegakan syariat Islam pada ranah multikulturalisme akan menjadi terbuka dengan sangat lebar. Tinggal bagaimana umat Islam berani untuk mengambil pilihan model gerakan yang tidak terjebak pada idealisasi masa lalu sebagaimana kebiasaan kaum fundamentalisme tak berwawasan ataukah ikut-ikutan terjebak pada bangunan utopia masa depan sebagaimana yang menjadi penyakit paten dari gerakan kiri yang kekanak-kanakan[2].
Wilayah yang memungkinkan lahirnya Islam Warna-Warni dengan jelas dan terang-terangan adalah wilayah seni. Sebagaimana dipahami oleh Martin Heidegger[3] bahwa seni, terutama puisi merupakan arena yang paling aman untuk penampakan ada, karena puisi merupakan sebuah interpretasi terhadap sang ada kedalam wilayah kultural, namun juga tidak sepenuhnya memberangus sifat natural yang merupakan sifat dasariah dari sang ada. Atau dalam bahasa Kuntowijoyo[4] bahwa seni mampu meruntuhkan mitos, dimana mitos merupakan abstraksi dari yang konkrit sementara seni membalikkan keadaan ini, karena seni justru merupakan upaya konkretisasi dari yang abstrak.
Jadi ujung tombak penegakan syariat Islam yang paling ramah dan tidak memberangus serta menelikung ranah multikulturalisme adalah seni. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya seluruh proses hidup manusia merupakan tindakan seni kalau kau memahaminya melalui penghayatanmu yang mendalam. Camkan itu.
Multikultural, menurut Ahmad Baso1, berwujud menjadi sebuah gerakan. Dengan defenisi seperti ini, maka multikultural harus bisa dibedakan dengan realitas budaya yang plural. Multikultural merupakan sebuah proyek atau usaha sadar untuk mengatur dan mendinamisasi hubungan (relation) antar kultur, sementara plural hanyalah sebuah kondisi yang sudah ada sebagai realitas. Dengan demikian --masih menurut Ahmad Baso, gerakan multikulturalisme merupakan proyek multidimensional yang melibatkan berbagai etnis dan berbagai macam kegiatan.
Sementara itu, Yasraf Amir Piliang2 mengatakan bahwa multikulturalisme adalah sebuah relasi pluralitas yang di dalamnya terdapat problem minoritas (minority groups) vs mayoritas (mayority group), yang di dalamnya ada perjuangan eksistensial bagi pengakuan, persamaan (equality), kesetaraan, dan keadilan (justice). Beliau juga membedakannya dari pluralisme yang diartikannya sebagai pandangan yang menghargai kemajemukan, serta penghormatan terhadap sang lain yang berbeda (the others), membuka diri terhadap warna-warni keyakinan, kerelaan untuk berbagi (sharing), keterbukaan untuk saling-belajar (inklusivisme), serta keterlibatan diri secara aktif di dalam dialog dalam rangka mencari persamaan-persamaan (common belief) dan menyelesaikan konflik-konflik.
Lebih jauh, multikultural menjadi ranah tempat berlangsungnya komunikasi, dialektika dan tawar-menawar antarbudaya yang terjadi secara seimbang dan sederajat dalam hal hak-hak dan kewajiban-kewajiban kultural. Bila memang demikian adanya, satu hal yang menarik dalam perbincangan multikulturalisme dalam bingkai kelokalan kita adalah wacana penegakan syariat Islam sebagai sebuah aspirasi kultural yang sedang hangat mencari ruang eksisten.
Dengan wacana multikulturalisme, maka keinginan untuk menegakkan syariat Islam akan mendapat ruang perbincangan yang lebih akademis dan bisa di pertangungjawabkan secara ilmiah. Multikulturalisme menghendaki kedewasaan dalam menyikapi perbedaan dan keanekaragaman yang ada, namun juga berusaha untuk tidak terjebak pada affirmative action yang merupakan penyelewengan dari multikulturalisme.
Multikulturalisme dan Ancaman Kegagalan
Multikulturalisme sebagai sebuah konsep dan tawaran solutif atas berbagai problem sosial, di atas kertas memang memiliki jaminan perbaikan, namun secara inhern, tidak bisa dinafikan adanya ambiguitas di dalamnya. Seperti disinyalir oleh Manneke Budiman3, ada tiga hal yang harus diwaspadai dalam multikulturalisme, yaitu; pertama, ketika multikulturalisme bergeser menjadi ideologi, maka multikulturalisme yang pada mulanya merupakan arena kontestasi, pada titik ini juga menjadi pemain. Pertanyaan yang patut di ajukan adalah mungkinkah multikulturalisme tetap konsisten untuk majemuk, terbuka dan akomodatif dalam arena kontestasi ideologi.
Kalaupun pertanyaan pertama terjawab, pertanyaan
kedua yang menjadi masalah multikuturalisme adalah mungkinkah multikulturalisme
menang tanpa menggunakan strategi penyingkiran dan pembungkaman terhadap yang
lain. Sementara itu sebagaimana mafhum, ideologi cenderung untuk menyingkirkan
dan membungkam lawan-lawannya, hal ini karena ideologi selalu bersifat ekslusif
dan tertutup.
Masalah kedua dalam multikulturalisme menurut Manneke adalah ketika multikulturalisme mengalami penyelewengan dan dimanfaatkan untuk menumbuhkan semangat chauvinisme, sukuisme, dan tirani minoritas. Hal ini akan berakibat muncul dan lahirnya sebuah struktur sosial baru yang cendrung memanjakan dan memberi hak khusus kepada kelompok minoritas yang selama ini terbungkam dan terpinggirkan.
Dan problem yang ketiga adalah pemahaman multikulturalisme mengalami reduksi sebagai sekadar kondisi plural, seperti di Indonesia. Kalau pembahasan ini coba dibatasi pada ruang lingkup Indonesia, maka akan ditemukan adanya penyimpangan ini secara nyata. Baik pada persoalan kultural secara luas, maupun pada persoalan agama secara spesifik.
Penyelewengan multikulturalisme menjadi sekadar pluralisme yang terjadi di Indonesia, terutama pada wilayah keagamaan, ini lebih merupakan akibat dari bangunan teologi yang berkembang. Ini pula yang menjadi kendala perguliran wacana syariat Islam. Meminjam pembagian corak teologi Cecelia Lynch4, akan ditemukan betapa corak teologi seseorang atau sebuah komunitas keagamaan maupun kultural akan sangat berpengaruh bagi proyek multikulturalisme.
Corak teologi Cecelia itu adalah pertama, teologi eksklusif. Teologi ini merupakan teologi yang paling ideologis, sifatnya sangat tertutup dan menempatkan teologinya sebagai satu-satunya kebenaran. Kedua, teologi apologetik. Model teologi apologetik tidak se-ekstrim teologi eksklusif, namun mereka tetap berusaha menjelaskan bahwa teologi merekalah yang benar dengan berusaha mencari berbagai macam apologi atau sistem pembenaran.
Ketiga, teologi inklusif. Dalam teologi seperti ini, sudah ada ruang pengakuan terhadap teologi di luarnya, namun kesimpulan akhir akan kebenaran tetap kembali pada dirinya. Teologi lain memang memiliki kebenaran, tetapi intensitas kebenaran teologi lain tetap berada di bawah kebenaran teologinya. Keempat, teologi sinkretis. Teologi yang paling nyeleneh dan cendrung menyederhanakan masalah kebenaran, karena menganggap semua teologi sama saja sehingga lebih baik dan sah bila antar teologi itu ada perkawinan dan pembauran konsep.
Terakhir, kelima¸ teologi pluralis. Teologi model inilah yang paling pas untuk terbangunnya proyek multikulturalisme. Hal ini karena teologi model ini mengakui bahwa setiap teologi memiliki eksistensi masing-masing, namun semuanya berada dalam tahap proses, sehingga dinamisasi dan dialektika yang terwujud dalam bentuk kontestasi dan dialektika antar teologi lebih memungkinkan.
Kalau pemetaan teologi Cecelia Lynch dipakai dalam menyorot bangunan teologi masyarakat Indonesia yang berusaha menegakkan Syariat Islam secara formal, umumnya masih menganut corak teologi eksklusif. Sementara itu sebagian kecil umat Islam yang berpikir inklusif, apologetik bahkan sinkretis, tidak terlalu ngotot, bahkan tema syariat Islam secara formal bukanlah menjadi hal yang urgen bagi mereka. Bahkan kelompok Islam minoritas ini memiliki siasat tersendiri untuk berislam tanpa harus terjebak pada formalisasi syariat.
Kuntowijoyo5, dengan menganalisis kategori-kategori sistem pengetahuan dan formasi sosial, menemukan fase perkembangan umat Islam Indonesia dan merumuskannya dalam sebuah periodisasi sejarah. Periode pertama, beliau menamainya sebagai periode mitos, umat Islam didominasi oleh kesadaran kawulo. Periode kedua, adalah periode ideologi, umat Islam di indonesia masih di“halusinasi” oleh kognisi wong cilik.
Pada periode terakhir, ketiga, mengemuka periode ilmu. Periode ini ditandai dengan masuknya wabah pencerahan Eropa ke Indonesia pada awal abad 20 M. kesadaran yang diinternalisasi umat Islam adalah kesadaran kewargaan. Nah, kalau berbicara model kesadaran mana yang paling potensial untuk sebuah penegakan syariat Islam secara dewasa, maka jawabnya tentu pada kesadaran kewargaan yang berada pada periode ketiga.
Namun sayang sekali karena dampak dari bangunan teologi yang dianut, maka geliat formalisasi syariat Islam yang mengemuka akhir-akhir ini adalah gerakan yang berbasis pada kesadaran yang ideologis. Kalaupun ada upaya menggiringnya menjadi kesadaran kewargaan, itupun hanya bermain pada tataran elite. Sehingga kesadaran umat secara umum masih tetap pada taraf ideologi yang tentunya berjalin berkelindan dengan teologi yang eksklusif.
Bila sudah seperti ini kondisi yang melingkupinya, maka formalisasi syariat Islam, terancam mengalami kegagalan, bahkan dalam sebuah ruang kontestasi yang demikian terbuka yang ditawarkan oleh proyek multikulturalisme. Hal ini karena di dalam bangunan kognisi umat Islam hari ini secara inhern memang termuat ambiguitas konsepsional ketika diperhadapkan dengan wacana multikulturalisme. Wajah umat Islam dengan versi syariat Islam yang di tawarkan akan menyeret wacana multikulturalisme pada jurang bunuh diri.
Dengan nyata akan terlihat bagaimana potensi ambiguitas multikulturalisme akan menjadi kenyataan karena dorongan dan desakan wajah Islam yang ditawarkan, sehingga multikulturalisme akan berakhir dan mengalami proses kematian yang tragis. Sebuah bunuh diri yang nyata. Hasil mimikri6 budaya antara Islam dan multikulturalisme akan melahirkan sebuah masyarakat nekrokultur6.
Mimikri Baru Islam-Multikultural
Upaya penyelamatan terhadap bangunan sosial mutlak harus dilakukan, oleh karena itu gerak masyarakat kearah nekrokultur mutlak harus di hentikan. Namun satu hal yang harus di catatbahwa, untuk menyelamatkan konstruksi sosial, bukanlah dengan cara memberangus hasrat masyarakat untuk melakukan formalisasi syariat Islam ataukah menghentikan proyek multikulturalisme. Karena pemberangusan dan pembungkaman akan melahirkan sebuah bangunan nekrokultura baru. Yang patut dilakukan adalah melakukan mimikri ulang secara kultural terhadap Islam dan multikultural.
Langkah ini dapat dilakukan dengan dua fase. Fase pertama merupakan fase reinterpretasi atas teologi umat Islam dari teologi eksklusif ke arah teologi pluralis, dengan cara “menyeret” umat untuk beranjak dari periode mitos dan ideologi menuju periode ilmu. Untuk membantu usaha ini, tawaran Kuntowijoyo, merupakan tawaran yang menarik untuk di pertimbangkan.
Kuntowijoyo7 menawarkan sebuah konsep “Ilmu Sosial Profetis”, inti dari konsep ini adalah, pertama, melakukan transformasi sosial dan perubahan dengan cara menjelaskan fenomena sosial kemudian mengubahnya, di samping itu, memberikan interpretasi, mengarahkan, serta membawa perubahan bagi pencapaian nilai-nilai yang dianut oleh kaum muslimin sesuai petunjuk Al-Qur’an, yakni emansipasi atau humanisasi, liberasi, dan transendensi8.
Kemudian, inti kedua dari Ilmu Sosial Profetik adalah bagaimana menjadikan al Quran sebagai paradigma. Hal ini ditawarkan oleh Kuntowijoyo melalui sebuah proyek yang digelarinya “Strukturalisme Transendental”. Menurutnya, setiap relitas sosial selalu dikonstruksi oleh mode of thought atau mode of inquiry. Mode of thought mengkonstruksi realitas melalui mode of knowing yang dilahirkannya. Sebuah cara berfikir yang mirip dengan analisis episteme9 Foucauldian.
Disamping itu, satu hal yang sangat penting untuk dilakukan secara internal oleh umat Islam adalah proses desakralisasi kebenaran. Proyek ini menjadi penting, karena bila ini tidak pernah terlaksana, maka selamanya Islam akan dipahami secara eksklusif. Kebenaran yang selama ini terdedahkan di tengah-tengah umat harus bisa dipahami sebagai sekadar hasil konstruksi episteme tertentu. Bahkan, karena kebenaran hanyalah sebagai sebuah produk dari metode interpretasi tertentu, maka maknanya senantiasa tertunda10.
Bila penyelamatan telah dilakukan pada sisi umat Islam, maka sisi yang satunya, yaitu multikulturalisme, juga seharusnya mengalami penyelamatan. Homi Bhabha11 mengatakan bahwa kata “kultur” dalam multikulturalisme, seharusnya jangan dipahami sebagai suatu rujukan identitas yang bersifat apriori, melainkan sebagai aktivitas negosiasi, pengaturan, dan pengesahan tuntutan-tuntutan akan representasi diri yang kolektif, yang tidak hanya saling berkompetisi, namun juga kerap saling bertubrukan12.
Pemahaman seperti ini harus terbangun untuk menghindari membekunya konsep multikulturalisme menjadi segepok ideologi. Di samping itu untuk menahan agar multikulturalisme tidak terjatuh pada sekadar menjadi bangungan pluralisme, maka masih menurut Bhabha, sifat hubungan antar unsur yang terlibat dalam aktivitas itu adalah konfliktual dan kompetitif, bukan harmonis dan konseptual13. Bila semuanya dipahami sebagai konflik dan kompetisi, maka akan ditemukan bahwa multikuluralisme merupakan sesuatu yang hidup dan penuh gairah, serta bukan sekadar sebuah gambaran realitas yang membeku.
Dengan meminjam analisis Kritik Ideologi Jurgen Habermas14, kemudian diperuncing oleh oto-kritik atas multikulturalisme, Cornel West15 menganjurkan agar multikulturalisme jangan dipahami sebagai ideologi, melainkan sebagai sebuah kritik yang mampu menyoroti berbagai persoalan yang terkandung di dalam multikulturalisme sendiri16. Multikulturalisme di samping dipahami sebagai subyek/pelaku analisisi sosial, multikulturalisme juga harus dijadikan sebagai obyek analisa, karena multikulturalisme juga merupakan konsep yang tidak bisa lepas dari konteks sosial maupun historis tertentu.
Islam Warna-Warni, Islam Lokalitas
Bila upaya membangun mimikri baru Islam-Multkultural berhasil, maka akan lahir sebuah wajah syariat Islam yang tidak memberangus multikulturalisme. Bahkan akan lahir sebuah wajah Islam Warna-Warni. Islam-Multikultural akan mengedepankan local content dalam melakukan interpretasi terhadap Islam. Islam yang bercorak lokalitas akan memungkinkan lahirnya kontestasi budaya lokal dari rahim Islam-Multikultural. Islam Warna-Warni ini akan menolak logika kesamaan dan proses asimilasi yang satu arah.
Ada beberapa nilai dasar yang menjadi ciri khas dari Islam Warna-Warni yaitu, pertama tanpa sentrum, kedua, merupakan hasil penghayatan atas local content. Ketiga, berwujud pengetahuan non-diskursif atau kesadaran non-reflektif. Keempat, berlandaskan pada aqidah yang berorientasi praxis-pragmatis. Kelima, merupakan teologi proses.
Islam yang tanpa sentrum memungkinkan merumuskan sebuah bangunan syariat Islam yang tidak berkiblat ke Arab. Jadi ada upaya untuk memisahkan antara nilai Islam dari budaya Arab yang selama ini menjadi ibu kandungnya. Seuah ikhtiar melahirkan interpretasi Islam dalam pangkuan budaya lokal. Islam Warna-Warni memotong model asimilasi budaya satu arah, bahwa untuk menjadi Islam, maka harus menjadi Arab. Posisi Arab sebagai sentrum kebenaran dari nilai Islam harus mengalami delegitimasi dengan mengedepankan penafsir-penafsir lokal yang lebih memahami nalar dan kognisi masyarakat lokal.
Islam Warna-Warni akan mendorong penguatan wilayah feri-feri tanpa harus terjebak pada affirmative action yang cenderung melahirkan kekuasaan otoritatif seorang penafsir sebagai kebenaran tunggal secara apriori dan mutlak. Sebagaimana mafhum, proses representasi menurut Nuhsin Arbabzadah-Green17 bukanlah realitas yang sebenarnya, ia hanya menghadirkan satu potongan atau esensialisasi dari realitas tersebut, yang terkadang penuh reduksi dan menggeneralisasi. Bila posisi setiap representasi adalah sama, maka Islam yang di representasikan oleh budaya Arab, tidak berhak untuk menjadi tafsir tunggal Islam.
Karena setiap bangunan budaya sebagai wilayah feri-feri punya hak yang sama untuk merepresentasikan Islam, maka tentu akan lahir Islam yang concern terhadap local content masing-masing budaya. Dengan terbukanya ruang ini, akan memungkinkan Islam menjadi sebuah ruang penghayatan spirtualitas yang betul-betul dialami secara utuh sebagai proses kemausiaan dalam sebuah proses kemenjadian oleh seorang manusia.
Proses penghayatan yang agak fenomenologi ini, akan mendorong lahirnya bangunan pengetahuan non-diskursif18, sebagai bangunan pengetahuan alternatif yang tidak di produksi oleh sebuah formasi diskursif dominan yang cendrung menghegemoni. Juga penghayatan ini akan melahirkan kesadaran non-reflektif19 sebagai model kesadaran yang tidak berjarak dengan realitas dan merupakan ikhtiar keluar dari belukar kesadaran ideologis yang mengekang dan membeku. Jadi Syariat Islam yang paling riil adalah yang aktual dan teraktualisasi di tengah masyarakat yang lahir dari hasil penghayatan atas realitas spiritual.
Islam Warna-Warni mendorong model aqidah praxis-pragmatis, maksudnya bahwa pada dasarnya tujuan utama dari aqidah adalah praxis atau pragmatis, bukan teoritis, argumentatif maupun retoris. Aqidah harus mampu menjadi landasan gerak dan menggerakkan. Tauhid sebagai doktrin dasar aqidah Islam sudah bukan saatnya lagi berbicara tentang keesaan Tuhan secara njlimet, namun lebih pada tuntutan bagaimana diktum ini mengejawantah dalam realitas lewat wajah kebenaran, keadilan dan spiritualitas.
Sebagaimana dikatakan oleh Abbe Pire20, apa yang menjadi persoalan bukanlah perbedaan antara orang yang beriman dan orang yang tidak beriman, akan tetapi antara siapa yang membela (menjalankan) dan siapa yang tidak membela atau tidak mengamalkan. Kebenaran Aqidah dari Islam Warna-Warni terletak pada tanggungjawab kulturalnya. Bukan pada kekuatan argumentasi kebenaran teoretisnya. Inilah aqidah praxis-pragmatis yang menjadi hakekat Syariat Islam.
Ciri terakhir dari Islam Warna-Warni adalah coraknya sebagai teologi yang hidup dan senantiasa berjalan sebagai proses tanpa henti. Teologi proses dimungkinkan karena indikator kebenaran sebuah teologi terletak pada kemampuannya untuk senantiasa menjawab kebutuhan realitas sosial, sementara itu sebagaimana mafhum, realitas sosial merupakan sesuatu yang hidup, senantiasa berada dalam situasi dan wajah konfliktual serta kompetitif. Kondisi ini menuntut sebuah bangunan kebenaran yang bersifat holistik dengan ciri situasi taksa, samar dan ambigu, namun bernuansa intuitif, mistisis dan lebih estetis[1].
Islam-Multikuluralisme Melalui Seni
Dengan wajah Islam yang warna-warni, maka kemungkinan penegakan syariat Islam pada ranah multikulturalisme akan menjadi terbuka dengan sangat lebar. Tinggal bagaimana umat Islam berani untuk mengambil pilihan model gerakan yang tidak terjebak pada idealisasi masa lalu sebagaimana kebiasaan kaum fundamentalisme tak berwawasan ataukah ikut-ikutan terjebak pada bangunan utopia masa depan sebagaimana yang menjadi penyakit paten dari gerakan kiri yang kekanak-kanakan[2].
Wilayah yang memungkinkan lahirnya Islam Warna-Warni dengan jelas dan terang-terangan adalah wilayah seni. Sebagaimana dipahami oleh Martin Heidegger[3] bahwa seni, terutama puisi merupakan arena yang paling aman untuk penampakan ada, karena puisi merupakan sebuah interpretasi terhadap sang ada kedalam wilayah kultural, namun juga tidak sepenuhnya memberangus sifat natural yang merupakan sifat dasariah dari sang ada. Atau dalam bahasa Kuntowijoyo[4] bahwa seni mampu meruntuhkan mitos, dimana mitos merupakan abstraksi dari yang konkrit sementara seni membalikkan keadaan ini, karena seni justru merupakan upaya konkretisasi dari yang abstrak.
Jadi ujung tombak penegakan syariat Islam yang paling ramah dan tidak memberangus serta menelikung ranah multikulturalisme adalah seni. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya seluruh proses hidup manusia merupakan tindakan seni kalau kau memahaminya melalui penghayatanmu yang mendalam. Camkan itu.
1 Baso,
Ahmad. Plesetan Lokalitas, Desantara. Jakarta. 2002. Cetakan I
2 Piliang.
Y. A. Neopluralisme , Belajar Dari Pluralisme Kecil. Artikel. Kompas
3 Budiman,
Manneke. Masih Adakah Masa Depan Bagi Multikulturalisme ? dalam Srinthil
edisi 4, Kajian Perempuan Multikultural
Desantara. Jakarta. 2003
4 Ali.
Muhammad. Teologi dan Multikulturalisme, Artikel. Kompas.
5 Kuntowijoyo.
Paradigma Islam, Interpretasi Untuk Aksi. Mizan. Bandung. 1991
6 Mimikri
adalah sebuah strategi budaya yang di tawarkan oleh Homi
Bhabha (1994) yang diartikan sebagai proses peniruan/peminjaman berbagai
elemen kebudayaan, disamping itu mimikri juga bisa di pandang sebagai strategi
menghadapi dominasi. Lebih lanjut, lihat Hibriditas, Antariksa dalam Kreolisasi,
dan Mimikri, artikel www.kunci.or.id
6 Nekrokultura
adalah sebuah model bangunan budaya yang cendrung pada kehancuran, kematian dan
destruktivitas.
7 Kuntowijoyo.
Muslim tanpa Masjid. Mizan. Bandung. 2001
8 Marzuki.
A. F. Membangun Semesta Budaya Profetik, Artikel. Kompas. 21 September
2003
9 Episteme
merupakan keseluruhan pola pikir yang berhubungan dengan sistem wacana yang
digunakan, institusi yang dimanfaatkan maupun posisi subjek dalam pemilihan
nilai yang dianutnya. Episteme membantu kita dalam mendefinisikan
realitas, sekaligus merekontruksinya. Penjelasan lebih lanjut, lihat Foucault, Michael, Power
Knowledge, Selected Interview and Other Writings, 1972-1977, the Harvester
Press, Sussex, 1980
10 Kondisi makna yang selalu tertunda,
di ulas secara gamblang oleh Jacques Derrida dengan konsep difference-nya.
Lebih lanjut silahkan baca Bertens, K. Filsafat Barat Kontempore Prancis,
Gramedia, Jakarta, Agustus 2001, Cet.
III. Hal
326-341
11 Bhabha. Homi. Reinventing Britain
; A Manifesto , dalam N. Wadham-Smith (ed). Brithish Studies Now Vol 9.
April 1997
12 Budiman. Manneke, op.cit.
13 Budiman. Manneke, ibid.
14 Fauzi. Ibrahim Ali. Jurgen
Habermas. Jakarta. Teraju. April 2003 Cetakan I
15 West. Cornel. Prophetic Thought
in Postmodern Times, dalam Beyond Eurocentrism and Multikculturalism,
volume 1 Monroe ; Common Courage Press. 1993
16 Budiman. Manneke, op.cit.
17 Wardani, Farah. Representasi
islam; Muslim di Barat, Islamophobia dan Multikulturalisme. Artikel.
Kompas, 26 oktober 2003
18 Foucault. Michael, Pengetahuan dan Metode, karya-karya
Penting Foucault, Jalasutra,Yogyakarta,2002
19 Fauzi. Ibrahim Ali. op.cit.
20 Fromm, Erich. Psikoanalisa dan
Agama. Jakarta. Atista. 1998 juga
Fromm. Erich. Manusia Menjadi Tuhan, Yogyakarta.
Jalasutra. Februari 2003. Edisi 2
[1] Heriyanto. Husein, Paradigma Holistik,
Teraju, Yogyakarta, 2003 Cetakan I
[2] Freire. Paulo. Pendidikan Yang Membebaskan,
Melibas. Jakarta Timur. 2001. Cetakan I
[3] Adian, Donny Gahral. Martin Heidegger,
Jakarta. Teraju. Maret 2003. Cet. I
[4] Marzuki. A. F. op.cit.